Zaman dahulu tekanan/ masalah yang dialami umat manusia lebih didominasi oleh hal-hal yang bersifat eksternal, yang berasal dari luar manusia. Misalnya ancaman wabah penyakit, ancaman kelaparan, dan perang berkepanjangan.
Di abad ke-21—dengan adanya riset bidang kedokteran yang makin canggih, demokratisasi dan perdamaian yang semakin meluas, kesejahteraan yang semakin meningkat—ancaman terhadap masalah-masalah eksternal tersebut sudah bisa teratasi. Makin tumbuhnya kemerdekaan berpendapat, keleluasaan berpikir, ketercukupan materi, ditunjang kecanggihan teknologi, semestinya mampu membuat hidup manusia lebih tenang dan tenteram. Namun begitu, yang terjadi justru sebaliknya. Kegundahan, kegelisahan, kesedihan, rasa was-was dan cemas justru kerap bergejolak dalam diri manusia. Tekanan/masalah internal inilah yang memicu stress. Meningkatnya stress ternyata juga mendongkrak angka kematian akibat bunuh diri. Krisis ekonomi AS tahun 2007, secara signifikan memukul perekonomian Jepang yang sangat bergantung pada ekspor mobil, mesin, dan peralatan IT. WHO melansir bahwa tahun 2008 angka bunuh diri di Jepang mencapai 30.000 jiwa, merupakan yang tertinggi di dunia. Sebagaimana diberitakan AFP Sabtu (26/12/2009), berdasarkan data Kepolisian Nasional Jepang, antara bulan Januari hingga November 2009 total 30.181 jiwa melakukan tindak bunuh diri di negeri sakura itu.
GOLDEN GATES : Tempat Favorit untuk Bunuh Diri
Di amerika serikat, Golden Gates yang selesai dibangun 1937 merupakan tempat favorit untuk bunuh diri. diperkirakan 1300 kasus bunuh diri berlangsung di jembatan ini.
Angka rata-ratanya adalah 1 kasus setiap dua minggu. Sedemikian banyaknya kasus bunuh diri – sampai-sampai pihak otoritas jembatan berhenti menghitung saat angka bunuh diri mencapai 1000 di tahun 1995. Sejak awal tahun 2005 saja, tercatat 20 kasus bunuh diri berlangsung di jembatan ini.
Sebagian dari kasus bunuh diri ini terekam di kamera yang dipasang di beberapa bagian jembatan saat seorang pembuat film dokumenter Eric Steel memasang kamera di tempat ini.
Penderitaan karena penyakit berkepanjangan, Himpitan ekonomi (kemiskinan), cobaan hidup dan tekanan lingkungan seringkali membuat manusia kehilangan kendali atas dirinya. Apabila keilmuan dan keimanan mereka tak sanggup menjawab masalah-masalah tersebut, akan timbul kekosongan dalam ruang jiwa. Mereka akan beranggapan bahwa hidup mereka tidak ada gunanya. Dan karenanya, hidup atau mati, bagi mereka tidak ada bedanya. Ketidakmampuan dalam memberikan makna hidup inilah yang menjadi pemicu utama manusia untuk bunuh diri.
ERA DIGITAL
Lahirnya sistem digital membuat teknologi berkembang luar biasa pesat. Bidang komputer, elektronika, telekomunikasi hingga penerbangan luar angkasa menjadi semakin berkembang. Teknologi digital ini muncul setelah ditemukan bilangan biner, yaitu angka nol dan satu sebagai sistem transformasinya.
Secara sederhana logika biner merangkum dua hal pokok : Logika OR dan Logika AND. Angka nol (o) bisa diartikan sebagai NO atau OFF. Sedangkan angka 1 berarti YES atau ON.
| Input | Ouput | |
| A | B | Z |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
Logika ini akan bernilai 1 jika salah satu atau kedua nilai inputnya (A & B) bernilai 1.
Jika logika di atas dimanifestasikan ke dalam logika kesuksesan, maka logika OR :
| Jalan | Paradigma | |
| A | B | Sukses |
| Gagal | Gagal | Gagal |
| Gagal | Sukses | Sukses |
| Sukses | Gagal | Sukses |
| Sukses | Sukses | Sukses |
Dalam paradigma sukses, logika OR bisa disebut sebagai logika masih banyak jalan ke Roma. Ketika jalan kesuksesan tidak ditemukan di A, maka jalan sukses itu kemungkinan besar akan ditemukan di B. Bilapun tidak, masih ada C,D,E, dst. (Logika OR bisa dikembangkan untuk input yang tak terbatas, tak hanya A dan B).
| Input | Ouput | |
| A | B | Z |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
Logika ini akan bernilai 1 hanya jika kedua nilai inputnya (A & B) bernilai 1.
Jika logika di atas dimanifestasikan ke dalam logika kesuksesan, maka logika AND :
| Jalan | Paradigma | |
| A | B | Sukses |
| Gagal | Gagal | Gagal |
| Gagal | Sukses | Gagal |
| Sukses | Gagal | Gagal |
| Sukses | Sukses | Sukses |
Dari tabel di atas terlihat bahwa Paradigma kesuksesan menurut logika AND terjadi jika kita tak pernah gagal (Sukses di A dan sukses di B).
Dari dua logika tersebut, terlihat bahwa logika OR lebih fleksible daripada logika AND. Logika OR juga memuat lebih banyak kemungkinan sukses. Karena itulah dalam troubleshooting kehidupan, sudah selayaknya logika OR dikedepankan daripada logika AND.
Kesuksesan dewasa ini bukan lagi didefinisikan sebagai ‘berada di puncak tujuan’, melainkan ‘proses perjalanan menuju puncak tujuan.’ Ibarat mendaki puncak gunung yang memakan waktu 5 jam, jika selama mendaki kita tak pernah merasakan kenikmatannya, maka hanya saat berada di puncak gunung itulah (max satu jam) kita merasakan kesuksesan pendakian. Lain halnya jika selama 5 jam pendakian kita menikmati pemandangan alam, merasakan lika-liku perjalanan dan merasakan kekompakan tim, maka sepanjang pendakian itulah kesuksesan kita.
Managing Partner sebuah biro hukum di Amerika serikat dikenal sebagai orang yang sangat sukses dan kaya raya. Namun begitu, ketika usianya menginjak 50 tahun, ia merasa sesuatu telah menggerogoti hidupnya. Ia memandang dirinya tak lebih sebagai budak waktu, yang hanya bekerja untuk memenuhi tuntutan para mitra dan kliennya. Keberhasilan baginya adalah sebuah ‘penjara’.
Banyak orang sukses lain telah berhasil meraih sasaran yang telah mereka tetapkan sendiri di usia 30-40an. Namun begitu mereka memandang ke depan, mereka seolah kehilangan orientasi sasaran. Mereka seperti merasa kering, seperti merasa ada kepingan yang menghilang dari dirinya.
Banyak orang yang merasa sudah mencapai cita-cita dan mencapai puncak kesuksesan, baik materi maupun karier/jabatan, tetapi kemudian merasakan “HAMPA dan KOSONG”. Mereka lalu menyadari bahwa mereka telah menaiki tangga yang keliru, justru setelah mencapai puncak tangga tertingginya!
Pada akhirnya mereka baru sadar bahwa uang, harta, kehormatan, harga diri atau kedudukan, bukanlah sesuatu yang mereka cari selama ini.
Manusia-manusia sukses tersebut tentu saja merupakan orang yang sangat bermanfaat secara sosial dan ekonomi bagi perusahaannya. Namun begitu, mereka kehilangan makna spiritual bagi dirinya. Spiritual Illness atau spiritual patology ini sering menjangkiti manusia modern. Contohnya presdir Hyundai, yang memilih bunuh diri dengan meloncat dari gedung pencakar langit. David Kellerman, Direktur keuangan Fredie Mac, juga diduga bunuh diri setelah perusahaan pembiayaan perumahan terbesar di AS itu mengalami kebangkrutan.
John Naisbit dan Patricia Aburdene dalam Megatrends 2000 mencatat bahwa banyak perusahaan multinasional dan perusahaan yang memproduksi merek-merek dunia telah mengeluarkan dana tidak kurang 4 Miliar dolar AS per-tahun untuk membayar para konsultan yang dikenal sebagai bagian kecenderungan spiritualitas baru, New Age. Sebanyak 67.000 pegawai Pasific Bell di California telah mengikuti pelatihan Krone, yakni sejenis pelatihan ala New Age ini.
Demikian pula halnya dengan perusahaan kelas dunia seperti Procter and Gamble, TRW, Ford Motor Company, AT&T, IBM, dan General Motors. Sejalan dengan itu, seperti diberitakan Asia Inc., January 1999, Mark Moody, pimpinan senior salah satu perusahaan minyak terbesar dunia Shell memutuskan untuk memanggil seorang pendeta Buddha terkemuka guna memberikan terapi spiritual kepada 550 ekskutif perusahaan tersebut. Dia menyatakan bahwa langkah ini diambilnya untuk meningkatkan kinerja karyawan perusahaan.
Dr. Gay Hendricks dan Dr. Kate Ludeman dalam buku The Corporate Mystic, secara lugas ingin menyatakan bahwa dalam era pasar global, Anda akan menemukan orang-orang suci, mistikus, atau sufi di perusahaan-perusahaan besar atau organisai-organisasi modern, bukan di wihara, kuil, gereja atau masjid. Dalam buku itu mereka menyatakan bahwa setelah bekerja dengan 800 orang eksekutif dalam 25 tahun terakhir ini, mereka mengajukan ramalan sebagai berikut: Para pengusaha yang sukses abad 21 akan menjadi para pemimpin spiritual.
Mereka akan merasa nyaman dengan kehidupan spiritualnya sendiri dan akan tahu cara memupuk perkembangan spiritual orang lain. Para pengusaha yang paling sukses pada zaman sekarang ini telah mempelajari rahasia ini. Bagi mereka yang telah beranggapan bahwa spiritual adalah bukan bagian dari sebuah bisnis, hanyalah menipu diri mereka sendiri begitu pula dengan orang-orang disekitarnya.
Menurut Hendricks dan Ludeman ada 12 ciri-ciri para Mistikus Korporat yaitu: Kejujuran Total, Fairness (Keadilan), Pengetahuan tetang diri sendiri, Fokus pada kontribusi, spiritualitas (Non-Dogmatik), Mencapai Lebih Banyak Hasil dengan Lebih Sedikit Upaya, Membangkitkan yang terbaik dalam diri mereka dan orang lain, keterbukaan terhadap perubahan, cita-rasa humor yang tinggi, visi jauh kedepan dan focus yang cermat, disiplin diri, yang ketat, dan keseimbangan.
MANUSIA DIGITAL
Cara terbaik membendung penyakit spiritual adalah dengan memperkuat fondasi spiritual. Landasan keimanan berperan penting untuk mengurai sejauh mana peran manusia dalam kehidupan. Nilai-nilai spiritual yang berbasis agama harus dikembangkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam buku ESQ Power, Ary Ginanjar menjelaskan bahwa di era digital manusia juga semestinya berpikir digital. Hal itu tercapai bila manusia bisa menjadi tulus dan ikhlas (0), karena berprinsip bahwa Tuhan (1), dan tidak menuhankan yang lainnya (0). Sebagaimana : Laa (0) ilaha illalloh (1).
Prinsip tulus dan ikhlas, sama halnya berpikir dan bertindak tanpa tendensi atau kepentingan (nol). Jika hal ini tercapai, maka akan muncul potensi yang tak terhingga. Inilah yang disebut sebagai manusia digital, yang mampu memunculkan potensi tak terhingga dalam dirinya (tak mudah putus asa untuk mencoba hal-hal baru) dengan tetap memegang nilai-nilai spiritualitasnya pada Tuhan Yang Esa.
Zaman dahulu tekanan/ masalah yang dialami umat manusia lebih didominasi oleh hal-hal yang bersifat eksternal, yang berasal dari luar manusia. Misalnya ancaman wabah penyakit, ancaman kelaparan, dan perang berkepanjangan.
Di abad ke-21—dengan adanya riset bidang kedokteran yang makin canggih, demokratisasi dan perdamaian yang semakin meluas, kesejahteraan yang semakin meningkat—ancaman terhadap masalah-masalah eksternal tersebut sudah bisa teratasi. Makin tumbuhnya kemerdekaan berpendapat, keleluasaan berpikir, ketercukupan materi, ditunjang kecanggihan teknologi, semestinya mampu membuat hidup manusia lebih tenang dan tenteram. Namun begitu, yang terjadi justru sebaliknya. Kegundahan, kegelisahan, kesedihan, rasa was-was dan cemas justru kerap bergejolak dalam diri manusia. Tekanan/masalah internal inilah yang memicu stress. Meningkatnya stress ternyata juga mendongkrak angka kematian akibat bunuh diri. Krisis ekonomi AS tahun 2007, secara signifikan memukul perekonomian Jepang yang sangat bergantung pada ekspor mobil, mesin, dan peralatan IT. WHO melansir bahwa tahun 2008 angka bunuh diri di Jepang mencapai 30.000 jiwa, merupakan yang tertinggi di dunia. Sebagaimana diberitakan AFP Sabtu (26/12/2009), berdasarkan data Kepolisian Nasional Jepang, antara bulan Januari hingga November 2009 total 30.181 jiwa melakukan tindak bunuh diri di negeri sakura itu.
GOLDEN GATES
Di amerika serikat, Golden Gates yang selesai dibangun 1937 merupakan tempat favorit untuk bunuh diri. diperkirakan 1300 kasus bunuh diri berlangsung di jembatan ini. Angka rata-ratanya adalah 1 kasus setiap dua minggu. Sedemikian banyaknya kasus bunuh diri – sampai-sampai pihak otoritas jembatan berhenti menghitung saat angka bunuh diri mencapai 1000 di tahun 1995. Sejak awal tahun 2005 saja, tercatat 20 kasus bunuh diri berlangsung di jembatan ini. Sebagian dari kasus bunuh diri ini terekam di kamera yang dipasang di beberapa bagian jembatan saat seorang pembuat film dokumenter Eric Steel memasang kamera di tempat ini.
MOTIF BUNUH DIRI
Penderitaan karena penyakit berkepanjangan, Himpitan ekonomi (kemiskinan), cobaan hidup dan tekanan lingkungan seringkali membuat manusia kehilangan kendali atas dirinya. Apabila keilmuan dan keimanan mereka tak sanggup menjawab masalah-masalah tersebut, akan timbul kekosongan dalam ruang jiwa. Mereka akan beranggapan bahwa hidup mereka tidak ada gunanya. Dan karenanya, hidup atau mati, bagi mereka tidak ada bedanya. Ketidakmampuan dalam memberikan makna hidup inilah yang menjadi pemicu utama manusia untuk bunuh diri.
ERA DIGITAL
Lahirnya sistem digital membuat teknologi berkembang luar biasa pesat. Bidang komputer, elektronika, telekomunikasi hingga penerbangan luar angkasa menjadi semakin berkembang. Teknologi digital ini muncul setelah ditemukan bilangan biner, yaitu angka nol dan satu sebagai sistem transformasinya.
Secara sederhana logika biner merangkum dua hal pokok : Logika OR dan Logika AND. Angka nol (o) bisa diartikan sebagai NO atau OFF. Sedangkan angka 1 berarti YES atau ON.
|
Input |
Ouput |
|
|
A |
B |
Z |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1 |
1 |
|
1 |
0 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
Logika ini akan bernilai 1 jika salah satu atau kedua nilai inputnya (A & B) bernilai 1.
Jika logika di atas dimanifestasikan ke dalam logika kesuksesan, maka logika OR :
|
Jalan |
Paradigma |
|
|
A |
B |
Sukses |
|
Gagal |
Gagal |
Gagal |
|
Gagal |
Sukses |
Sukses |
|
Sukses |
Gagal |
Sukses |
|
Sukses |
Sukses |
Sukses |
Dalam paradigma sukses, logika OR bisa disebut sebagai logika masih banyak jalan ke Roma. Ketika jalan kesuksesan tidak ditemukan di A, maka jalan sukses itu kemungkinan besar akan ditemukan di B. Bilapun tidak, masih ada C,D,E, dst. (Logika OR bisa dikembangkan untuk input yang tak terbatas, tak hanya A dan B).
|
Input |
Ouput |
|
|
A |
B |
Z |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1 |
0 |
|
1 |
0 |
0 |
|
1 |
1 |
1 |
Logika ini akan bernilai 1 hanya jika kedua nilai inputnya (A & B) bernilai 1.
Jika logika di atas dimanifestasikan ke dalam logika kesuksesan, maka logika AND :
|
Jalan |
Paradigma |
|
|
A |
B |
Sukses |
|
Gagal |
Gagal |
Gagal |
|
Gagal |
Sukses |
Gagal |
|
Sukses |
Gagal |
Gagal |
|
Sukses |
Sukses |
Sukses |
Dari tabel di atas terlihat bahwa Paradigma kesuksesan menurut logika AND terjadi jika kita tak pernah gagal (Sukses di A dan sukses di B).
Dari dua logika tersebut, terlihat bahwa logika OR lebih fleksible daripada logika AND. Logika OR juga memuat lebih banyak kemungkinan sukses. Karena itulah dalam troubleshooting kehidupan, sudah selayaknya logika OR dikedepankan daripada logika AND.
Kesuksesan dewasa ini bukan lagi didefinisikan sebagai ‘berada di puncak tujuan’, melainkan ‘proses perjalanan menuju puncak tujuan.’ Ibarat mendaki puncak gunung yang memakan waktu 5 jam, jika selama mendaki kita tak pernah merasakan kenikmatannya, maka hanya saat berada di puncak gunung itulah (max satu jam) kita merasakan kesuksesan pendakian. Lain halnya jika selama 5 jam pendakian kita menikmati pemandangan alam, merasakan lika-liku perjalanan dan merasakan kekompakan tim, maka sepanjang pendakian itulah kesuksesan kita.
Managing Partner sebuah biro hukum di Amerika serikat dikenal sebagai orang yang sangat sukses dan kaya raya. Namun begitu, ketika usianya menginjak 50 tahun, ia merasa sesuatu telah menggerogoti hidupnya. Ia memandang dirinya tak lebih sebagai budak waktu, yang hanya bekerja untuk memenuhi tuntutan para mitra dan kliennya. Keberhasilan baginya adalah sebuah ‘penjara’.
Banyak orang sukses lain telah berhasil meraih sasaran yang telah mereka tetapkan sendiri di usia 30-40an. Namun begitu mereka memandang ke depan, mereka seolah kehilangan orientasi sasaran. Mereka seperti merasa kering, seperti merasa ada kepingan yang menghilang dari dirinya.
Banyak orang yang merasa sudah mencapai cita-cita dan mencapai puncak kesuksesan, baik materi maupun karier/jabatan, tetapi kemudian merasakan “HAMPA dan KOSONG”. Mereka lalu menyadari bahwa mereka telah menaiki tangga yang keliru, justru setelah mencapai puncak tangga tertingginya!
Pada akhirnya mereka baru sadar bahwa uang, harta, kehormatan, harga diri atau kedudukan, bukanlah sesuatu yang mereka cari selama ini.
Manusia-manusia sukses tersebut tentu saja merupakan orang yang sangat bermanfaat secara sosial dan ekonomi bagi perusahaannya. Namun begitu, mereka kehilangan makna spiritual bagi dirinya. Spiritual Illness atau spiritual patology ini sering menjangkiti manusia modern. Contohnya presdir Hyundai, yang memilih bunuh diri dengan meloncat dari gedung pencakar langit. David Kellerman, Direktur keuangan Fredie Mac, juga diduga bunuh diri setelah perusahaan pembiayaan perumahan terbesar di AS itu mengalami kebangkrutan.
MANUSIA DIGITAL
Cara terbaik membendung penyakit spiritual adalah dengan memperkuat fondasi spiritual. Landasan keimanan berperan penting untuk mengurai sejauh mana peran manusia dalam kehidupan. Nilai-nilai spiritual yang berbasis agama harus dikembangkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam buku ESQ Power, Ary Ginanjar menjelaskan bahwa di era digital manusia juga semestinya berpikir digital. Hal itu tercapai bila manusia bisa menjadi tulus dan ikhlas (0), karena berprinsip bahwa Tuhan (1), dan tidak menuhankan yang lainnya (0). Sebagaimana : Laa (0) ilaha illalloh (1).
Prinsip tulus dan ikhlas, sama halnya berpikir dan bertindak tanpa tendensi atau kepentingan (nol). Jika hal ini tercapai, maka akan muncul potensi yang tak terhingga. Inilah yang disebut sebagai manusia digital, yang mampu memunculkan potensi tak terhingga dalam dirinya (tak mudah putus asa untuk mencoba hal-hal baru) dengan tetap memegang nilai-nilai spiritualitasnya pada Tuhan Yang Esa.



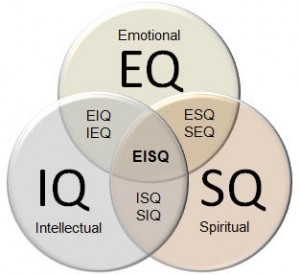
![[UNSET]](https://supersuga.files.wordpress.com/2009/04/unset.png?w=500&h=279)